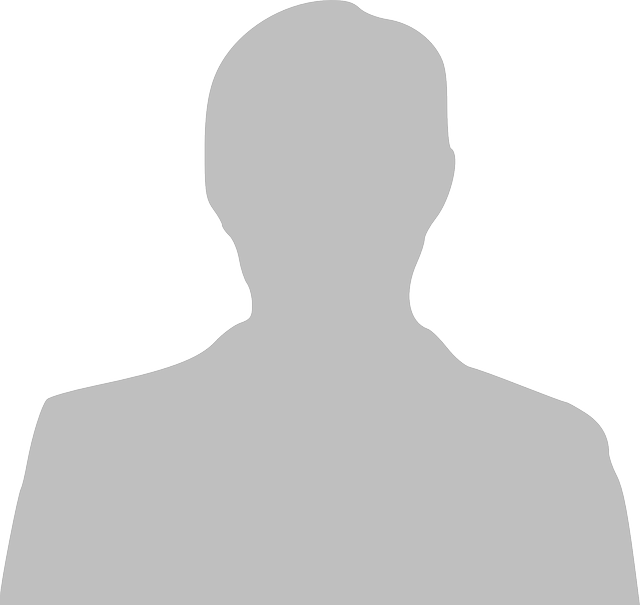Opini
Melawan Penjinakan Kebebasan Berpikir
Oleh I Ngurah Suryawan*
PENJINAKAN kebebasan berpikir dan praksis intelektual memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1965, banyak intelektual dan pemikir yang progresif, yang di-PKI-kan (baca: dikomuniskan) hilang dalam masa-masa gelap pembantaian massal. Warisan intelektualitasnya pun dianggap haram dipelajari apalagi diwariskan kepada anak cucu. Itulah yang disebut dengan praktik penjinakan. Terdapat beragam cara dalam praktik penjinakan ini, mulai dari kekerasan, pendisiplinan “ideologisasi”, hingga pemasungan karir akademik. Campur tangan politik kekuasaan dalam kebijakan pembatasan dan normalisasi kampus sesungguhnya adalah praktik penjinakan yang berupaya mengingkari kebebasan ekspresi dan kebebasan akademik (Wiratraman 2021).
Tak terkecuali Bali, pulau seribu pura sejuta ruko ini. Sejarah panjang politik kebudayaan Bali tidak bisa dilepaskan dari Tragedi 1965, di mana kekerasan dan pelenyapan manusia menjadi sisi gelap dan tahun yang tak pernah berakhir (Robinson 1995: 2006; Santikarma 2000; Suryawan 2007). Landasan kebudayaan Bali ke depannya dibangun di atas fondasi pelenyapan kisah-kisah Bali pada masa 1965. Kisah-kisah tentang Tragedi 1965 dihapus dari “representasi resmi” karena promosi otoritatif tentang Bali pasca-1965 adalah daerah yang aman dan damai, yang siap melayani semua keinginan wisatawan. Citra-citra Bali yang dikonstruksi oleh rezim Orde Baru tidak hanya diproduksi untuk konsumsi orang luar. Citra-citra tersebut dijadikan sebagai “modal budaya” untuk kepentingan pariwisata. Konstruksi yang kolonialistik itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan sang kuasa membentuk yang sering disebut dengan “rezim kebenaran”.
Baca juga:
https://balinesia.id/read/pandemi-kita-butuh-voice-bukan-noice
Santikarma (2000) dengan satir mengungkapkan untuk menarik devisa, kesusahan hidup petani disulap menjadi foto sawah yang hijau dan indah. Pemandangan di tebing jurang, yang sayangnya telah dikuasai oleh investor asing bekerjasama dengan masyarakat setempat, menjadi lokasi selfie (swafoto). Beban kaum perempuan yang kerja keras untuk keluarga suami mereka dengan berdagang, bertani, dan membuat banten (sesajen) untuk ritual, menjadi lukisan gadis cantik yang mempesona. Ekspresi kekerasan dan keliaran menjadi tarian Keris Dance yang secara rutin berlangsung sebelum pariwisata Bali dihantam pandemi Covid-19.
Saya ingin menunjukkan bahwa titik tolak politik kebudayaan Bali pasca-1965 sangat dipengaruhi oleh apa yang disebutkan oleh Santikarma (2000) sebagai trio sakti yaitu trauma kekerasan 1965, pariwisata, dan rezim pembangunan. Ketiga nilai-nilai itulah yang memastikan suksesnya program-program pemerintah dari program KB (Keluarga Berencana), kampanye sadar wisata, Adipura, kuningisasi sampai jambanisasi. Dengan menerima segala bentuk pemberian dan petunjuk dari penguasa, itu berarti rasa malu dan takut menjadi rasa bangga dan aman.
Jika sebelumnya terjadi pembungkaman dalam kebebasan berekspresi dan berpikir, kini yang terjadi adalah penjinakan dengan cara yang halus, penuh tata krama dan sopan santun, canggih, dan tampak mengayomi. Saya berargumen, rentang panjang pembungkaman ataupun penjinakan kebebasan berpikir tidak bisa dilepaskan dari Tragedi 1965, saat gerakan politik progresif dibersihkan dari akar-akarnya memulai reorganisasi kekuasaan pembangunanisme. Pada momen inilah kita bisa bercermin gerakan politik progesif pernah hadir namun kemudian absen hingga kini (Mudhoffir 2020: 26). Tragedi kelam pada tahun yang tidak pernah berakhir dalam sejarah Indonesia itu menyimpan begitu banyak tabir relasi kekuasaan di dalamnya. Salah satu yang terpenting saya kira adalah genealogi pembungkaman kebebasan berpikir dan berekspresi yang terus terwariskan hingga kini.
Baca juga:
https://balinesia.id/read/perpanjangan-ppkm-babak-a-khir-penanganan-covid-19
Penjinakan Universitas?
Apakah usaha penjinakan berpikir dan kebebasan akademik berlangsung di universitas? Bagaimana insan akademik ini memahami kebebasan tersebut dalam relasinya dengan kepentingan ekonomi politik? Apakah memprofessionalkan diri termasuk menjinakkan diri sendiri secara sadar untuk kuasa ekonomi politik? Lalu bagaimana peran universitas? Apakah universitas mampu menjadi ruang kebebasan berpikir itu berkembang untuk menjadi gerakan pemikiran akademik yang progressif? Atau masih menjadi monumen kelas menengah yang berada di menara gading?
B.S Mardiatmadja SJ dalam bukunya Komunitas Belajar (2017) mengajukan ide yang menyegarkan meski bukan baru. Baginya, universitas harus menghilangkan sekat dan jaraknya sebagai universitas doctorum et studentium (keseluruhan orang terpelajar dan sedang belajar). Nama universitas menunjukkan bahwa orang-orang yang tersangkut di dalamnya tidak mau bernikmat-nikmat dalam laboratorium individualnya atau dari sudut lain dipenjarakan dalam keterkotakan (pengetahuan, atensi, dan keilmuan atau keprihatinannya), melainkan mau membuka diri pada kepentingan universal.
Universitas semestinya memberikan perhatian pada bonum commune yang artinya adalah hal baik (kesejahteraan) dengan demikian juga keadilan, yang sifatnya umum (bukan hanya bagi sekelompok orang atau suatu lapisan orang saja; apalagi suatu ideologi tertentu). Bonum commune terdapat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menyangkut segala segi hidup sosial maupun kebudayaan.
Pendidikan tinggi dengan demikian berusaha untuk melayani agar segala aspek kebudayaan manusia diwariskan dan dikembangkan secara terintegrasi dalam pribadi manusia maupun dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, masa depan suatu bangsa amat tergantung dari proses didik yang sebagian dilayani oleh universitas. Universitas berfungsi dalam proses pewarisan dan pengembangan kebudayaan baik untuk pribadi yang tersangkut maupun untuk kesejahteraan seluruh masyarakat; dank arena itu bagi ”kesejahteraan seluruh rakyat” (Mardiatmadja SJ 2017: 30-31).
Situasi yang dimimpikan di atas tentu saja tidaklah mudah diwujudkan. Cita-cita bonum commune mendapatkan banyak tantangan. Tantangan tersebut tidak saja yang berasal dari usaha-usaha penjinakan yang dilakukan oleh sang kuasa bewajah negara, investasi, bahkan masyarakat dan universitas itu sendiri. Wiratraman (2021) dengan mengacu Edward Said dalam bukunya Peran Intelektual (1998) mengungkapkan bahwa ancaman khusus intelektual saat ini bukanlah otonomi kampus, bukan posisi pinggiran, bukan pula komersialisasi pendidikan yang mengerikan. Secara khusus ancaman intelektual itu ada pada dirinya sendiri yaitu perangai memprofesionalismekan dirinya sendiri. Profesionalisme adalah bahaya laten yang dapat menurunkan derajat intelektual seseorang, bekerja layaknya tukang yang dilakukan untuk penghidupan.
Baca juga:
https://balinesia.id/read/pokdarkamtibmas-bali-antara-pariwisata-dan-pertanian
Melawan dengan Bersolidaritas
Saya meyakini ada ruang kosong gagapnya universitas—yang sudah kadung melembaga dan menjadi birokratis—, alih-alih untuk menyediakan ruang solidaritas intelektual malah lebih sebagai penjara yang menyediakan menara untuk mengawasi insan akademiknya. Kampus kemudian mengalamai penjinakan dan menjadi pelayan kekuasaan. Perangai intelektualnya pun menjadi sangat feodalistik. Mereka inilah yang jamak ditemui dan melekat dalam birokrasi kampus dan memperlihatkan peran abdi kekuasaan. Intelektual hadir sebagai profesi, dan profesionalisme itulah yang jadi tameng justifikasi perannya (Wiratraman 2021).
Satu hal yang menjadi menarik untuk didiskusikan adalah bagaimana universitas mampu untuk menyediakan ruang bagi solidaritas intelektual tersebut? Sejarah panjang negeri ini cenderung buruk untuk menyediakan ruang bagi kebebasan akademik. Lebih buruk lagi, pembungkaman kebebasan akademik kini dilakukan dengan cara yang sangat canggih bernama birokratisasi dan profesionalisme intelektual.
Tendensi utama dunia akademik terbagi menjadi dua di internal kampus. Pertama, menyelami karir birokrasi dan membantu memperkuat kuasa negara dengan menghubungkan diri dalam lingkaran politik di dalamnya. Kedua, terintegrasinya universitas dalam semesta kosmopolitanisme pendidikan global. Konsekuensi dari kedua kecenderungan ini adalah berkurangnya advokasi pengetahuan pada ranah kuasa masyarakat sipil. Tepat di wilayah inilah peran social intelektual sangat dibutuhkan (Kusman, 2021).
Di tengah situasi yang membelenggu tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dengan penciptaan tata universitas yang membangun bersama intellectual solidarity (solidaritas intelektual). Seluruh tata dan pranata universitas harus mengungkapkan dan membangun solidaritas intelektual. Menjadi anggota universitas membutuhkan komitmen pada solidaritas intelektual. Dengan demikian akan terjalin jaringan ilmuwan dan mengabdi pada kesejahteraan bersama melalui komitmen intelektualnya. Solidaritas itu terbuka, artinya mengjangkaumelintasi batas-batas ilmu dan bahkan juga batas universitas. Secara radikal, solidaritas malah perlu melintasi batas bangsa dan negara.
Solidaritas intelektual berdasar pada humanisme universal yang dalam dunia universitas memang memusatkan perhatian pada segi intelektualnya. Dengan demikian, pendidikan di universitas tidak perlu menjadi abstrak dan teoritis, tetapi justru bertumpu pada realitas mencari pemahamannya yang terdalam, baik perihal alam maupun manusia dengan segala deritanya. Universitas perlu membuka penelitian dan analisisnya pada permasalahan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, universitas perlu menerjemahkan komitmen solidaritas intelektual tersebut dalam organisasi dan prioritas program maupun focus-fokus penelitiannya (Mardiatmadja SJ 2017: 52-53).
Oleh sebab itulah, untuk menandingi profesionalisme intelektual, salah satu caranya melawan adalah dengan solidaritas intelektual. Gerakan-gerakan akademik cum solidaritas di internal kampus, bahkan antar kampus dan dengan gerakan social lainnya di tengah rakyat setidaknya akan menjadi oase di tengah keterpakuan kita melihat canggih dan sopan santunnya oligarki bermain dan tingkah polah pion-pion rezim neo-liberalisme yang melahap hutan-hutan komunitas adat di negeri ini.
_____________
*Penulis adalah Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Warmadewa Bali. Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).
______________________________
Kolom Opini Balinesia.id dihadirkan untuk memberi ruang pada khalayak pembaca. Redaksi menerima tulisan opini dalam bentuk esai populer sepanjang 500-1000 kata yang membicarakan persoalan ekonomi, pariwisata, sosial, budaya, maupun politik. Tulisan dapat dikirim ke email [email protected]. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi.