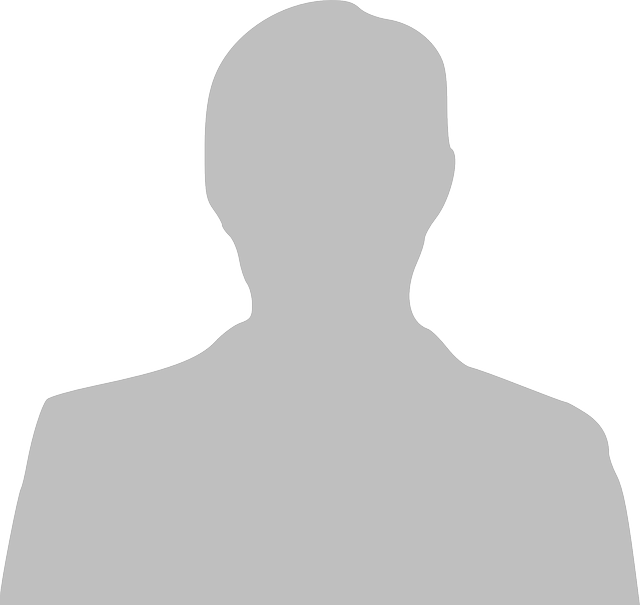Budaya
Kumbhakarna dan Lidah Tanpa Tuan
Oleh IK Eriadi Ariana*
Makweh tang ujar yukti dan/ atyanta iwênyatāt pituhun/ sep tang upadeśa ri kita/ apan mada darpānaputi//
Mwang dona nikang śabda hita/ swasthāni sawarganta kabeh/ sakweh pwa ikang wīra pêjah/ tāde kasulākên ta huwus//
Banyaklah perkataan yang patut dahulu/ namun sangat sulit untuk ditiru/ ilupakanlah segala petunjuk olehmu/ sebab dikungkung mabuk//
Dan, akan berpahala perkataan yang membahagiakan itu/ menyelamatkan keluargamu semua/ anyaklah para pahlawan itu mati/ apa yang dapat diperbuuat, terjadilah//
[Kakawin Ramayana Sargah XXII.21-22]
***
TIADA terkira hancur hati Kumbhakarna melihat sebagian ksatria Alengka telah gugur di medan laga. Keserakahan Rahwana, sang raja Alengka, yang menginginkan Sītā telah membuat rakyat sengsara. Rāma dengan para kera yang tak terkira jumlahnya menyerbu negeri para “raksasa”. Tujuannya hanya satu, mengembalikan kembali permata Ayodya ke tangan Rāmadewa.
Kumbhakarna kala itu terpasung pada dua kondisi yang begitu sulit. Ia tak memiliki persoalan dengan Rāma yang merupakan awatara Wisnu. Kumbhakarna tahu, berseberangan dengannya jelas akan berujung pada kebinasaan. Tapi, jika hanya diam melihat kawan dan kerabat terlahap panah-panah lapar Rāmadewa tentu adalah dosa yang lebih besar.
Kumbhakarna paham betul apa yang dilakukan Rahwana adalah kesalahan fatal. Ia pun meluapkan kekecewaannya pada Rahwana, kemudian membeber sejumlah ingatan kuno tentang kearifan yang diwariskan para leluhur. Ia mencoba menasihati kakaknya, meski tahu nasihatnya akan ditolak mentah-mentah oleh Sang Dasa Muka.
Demikianlah Kākāwin Rāmāyana mengisahkan kegundahan Kumbhakarna sebelum memutuskan bertempur untuk mempertahankan tanah air. Dalam kākāwin terpanjang dan terindah dalam khazanah sastra Jawa Kuno itu, pembaca dapat menyaksikan nasihat Kumbhakarna i dalam sejumlah guratan bait di sargah XXII—sebagaimana salah satunya ditulis sebagai pembuka tulisan kecil ini.
Pada episode itu, Kumbhakarna yang sebagian besar waktunya digunakan untuk “tidur” digambarkan layaknya yogin yang mengalirkan nasihat-nasihat suci pada kakaknya. Padahal, puluhan tahun sebelumnya ia justru tenggelam dalam zona tidur yang panjang karena terpeleset kata-kata.
Semua berawal di masa-masa mudanya, ketika ia, Rahwana, dan Wibhisana menggelar pertapaan hebat ke hadapan Dewa Brahma. Kisah hidupnya itu tergurat dalam Utara Kanda, kanda (bab) ketujuh Rāmāyana gubahan Rsi Walmiki.
Atas keteguhan tapa, masing-masing dari mereka berhak atas pahala. Rahwana memohon hidup abadi, namun itu menyalahi hukum Rta. Sebagai gantinya, ia diberikan anugerah tak terkalahkan, baik di kalangan dewa, manusia, asura, maupun makhluk lainnya. Wibhisana meminta agar senantiasa dianugerahkan kebijaksanaan. Anugerah inilah yang ia genggam, hingga memilih berpihak pada Rāma meski rakyat dan saudara-saudaranya musnah tak terkira.
Kumbhakarna yang perkasa, awalnya hendak meminta kesenangan yang abadi (suka sada). Dengan anugerah itu, ia tentu akan senantiasa termasyur, terlebih dengan kesaktiannya yang tiada tara. Jika anugerah itu turun, Kumbhakarna tak perlu susah-payah berupaya, sebab segala keinginan akan terpenuhi.
Mengetahui keinginan Kumbhakarna itu, para dewa di surga “membisik” Dewi Saraswati, sang dewi kata; dewi ilmu pengetahuan. Mereka memohon sakti Brahma ini untuk membalikkan lidah Kumbhakarna, sehingga “mala petaka” yang lebih besar dapat dihindari. Usulan yang lahir dari sudut pandang para dewa di surga itu akhirnya dikabulkan. Sebenarnya tidak adil, Kumbhakarna yang telah melakoni serangkaian tapa yang berat, namun ketika akan mendapat pahala justru “disabotase”. Itulah polarisasi dunia raksasa-dewa. Sejak masa silam mereka telah bertentangan. Pascaperistiwa pemutaran Giri Mandhara kedua ras ini jadi saling curiga, saling menjatuhkan jika ada kesempatan.
Mengabulkan permintaan para dewa, Dewi Saraswati kemudian bergegas menuju lidah raksasa yang berperawakan besar itu. Selanjutnya, dibelokkanlah kata “suka sada” yang hendak diminta ke hadapan Hyang Catur Muka menjadi kata “supta sada” yang berarti 'tidur abadi'. Hanya berbeda satu kata, dari suka ke supta, namun hal itu mengubah orientasi hidup Kumbhakarna. Ia kalah, senasib dengan leluhurnya yang tak tak mendapat jatah amreta layaknya para dewa meski sama-sama memutar Giri Mandhara.
Tidur ketika Gelap
Pembaca Rāmāyana umumnya akan mengangguk-angguk, menyetujui pembalikan kata-kata Kumbhakarna. Jawabannya sederhana, sebab raksasa adalah simbol kejahatan, hidupnya penuh dengan kekotoran, primitif, pemakan manusia, dan seterusnya. Raksasa adalah sumber kejahatan. Raksasa lawan dari dewa yang berperawakan tampan, bersinar, bijaksana, bahagia, dan seterusnya.
Namun, jika ditimbang lebih dalam dalam kasus pembalikan kata suka sada ke supta sada yang dilakukan Dewi Saraswati pada lidah Kumbhakarna, bukankah itu upaya mendiskriminasi ras raksasa? Model ini sejatinya masih terjadi hingga saat ini. Sebagai contoh, masyarakat “pedalaman” di suatu peradaban seringkali “direcoki” konsep yang mengklaim dirinya lebih modern, lebih maju, lebih layak bertahan di bumi yang kecil ini. Konsep-konsep yang mereka tawarkan adalah kesejatian yang abadi, padahal belum tentu peradaban pedalaman di masa sebelumnya adalah suatu keburukan, juga dosa bagi dunia. Begitulah dunia, berulang setiap zaman.
Kembali pada kasus Kumbhakarna dan lidahnya yang tanpa tuan. Pada pembacaan yang lebih netral, sebagian mungkin menyatakan bahwa pembelokan kata-kata Kumbhakarna terkait dengan ketidaksiapannya pada permintaannya sendiri.
Sebagai raksasa yang konon “cukup jauh dengan peradaban” dewa, mungkin ada sejumlah indikator yang belum terpenuhi. Ia harus melalui “ujian kompetensi” untuk bisa menyamakan derajatnya dengan para dewa. Tapa yang begitu kuat, kesaktian yang begitu dahsyat, kakayaan yang bergelimang, tidak cukup untuk bisa “naik kelas” ke alam dengan level lebih tinggi. Ia harus menghadapi musuh, dalam gelap malam yang pekat. Maka, dipilihlah jalan tidur untuk menguasai malam itu. Untuk menemui fajar, malam adalah jalan termutlak.
Apa yang lebih gelap dibandingkan diri sendiri? Dari semua hal yang paling rahasia dan pengetahuan yang paling digjaya, pemahaman tentang diri sendiri adalah yang paling sulit. Untuk menyingkap rahasia dan pengetahuan dalam diri yang mahaliar juga maha gelap itu, terlebih dahulu hendaknya dikalahkan musuh-musuh yang menguasainya. Dalam sejumlah pustaka, konon ada enam musuh yang bersemayam dan menyembunyikan secercah cahaya dalam diri, disebut sad ripu. Enam musuh yang berkoalisi “membajak” tubuh itu yakni kama (hawa nafsu, keinginan), loba (sifat tamak), kroda (sifat marah), moha (sifat bingung), mada (mabuk karena minuman keras), dan matsarya (sifat iri hati).
Dominasi keenam musuh itu semakin menjadi-jadi setelah berafiliasi dengan tujuh macam kegelapan, yang di dalam konsep Sanskertanya diistilahkan sapta timira. Sapta timira yang dimaksud adalah surupa (gelap hati karena wajah yang baik), dana (gelap hati karena bergelimang harta), guna (gelap hati lantaran merasa pandai), kulina (gelap hati karena keturunan), yowana (gelap hati karena masa muda yang enerjik), sura (gelap hati karena mabuk minuman keras), dan kasuran (gelap hati karena terlampau berani).
Jika tidur abadi adalah jalan yang dipilih Kumbakarna dalam memerangi musuh dan meningkatkan kualitasnya, dimana proses terjadi? Peperangan itu ada di dalam mimpinya yang tak pernah sekalipun pernah diungkap sang yogiswara. Tak ada yang pernah tahu apa yang dilakukan Kumbhakarna dalam tidur panjangnya, yang nyaris tak bisa dibangunkan. Pasukan Alengkapura yang ketika itu sedang susah bahkan harus menggunakan hewan perkasa semacam gajah dan berbagai senjata untuk membuka mata Kumbhakarna. Aneka makanan lezat yang disuguhkan juga tak mampu membuatnya meninggalkan tidurnya.
Berbeda dengan Kumbhakarna, masyarakat Hindu, khususnya di Bali memiliki sejumlah cara untuk menyerbu enam musuh dan menjemput fajar untuk memusnahkan tujuh gelap. Secara umum, masyarakat Bali modern menggantungkan peperangan itu pada berbagai ritual untuk meningkatkan kualitas diri . Ada yang melakukan palukatan, bayuh oton, dan seterusnya. Enam musuh yang sangat berbahaya itu juga secara simbolis dinyatakan lahir sebagai enam pasang gigi di mulutnya. Bagi masyarakat Hindu Bali, wajib hukumnya melakukan riual mapandes (dan istilah lainnya). Orang-orang yang lahir di hari tertentu, yang khusus dan riskan juga harus dinetralkan. Contoh orang yang lahir di Wuku Wayang diharapkan dapat mabayuh, agar tak dimangsa Batara Kala, sehingga hilang kesialan dan nasib buruk yang mengiringinya.
Sementara itu, bagi pemeluk jalan raja yoga pemusnahan terhadap musuh-musuh itu dilakukan dengan melakoni praktik yoga samadhi. Mereka berupaya menjerat indera dan pikiran yang liar. Konon, kesatuan tubuh dan unsur hidupnya ibarat seperti kereta. Badan adalah kereta, atma adalah penumpang, pikiran adalah kusir, sedangkan kudanya adalah lima kuda yang siap membawa badan ini kemana pun. Kuda-kuda itulah yang perlu dikuasai, sehingga enam musuh dapat ditumpas, sedangkan kegelapan tak mampu lagi menyentuh.
Bangun Tidur
Meski diinjak-injak dengan gajah-gajah perkasa, ditusuk beragam senjata runcing, dibangunkan dengan berbagai gendering musik, berbagai makanan minuman mengundang selera, Kumbhakarna tetap tidur dengan pulas. Istana tempat tidurnya sudah penuh sesak prajurit dan rakyat, sementara di luar istana keadaan semakin genting. Rama dan pasukan keranya terus saja menghujamkan berbagai senjata ke arah istana Rahwana.
Dalam kondisi terdesak itu, Rahwana hampir-hampir saja putus asa. Ia lantas menyatakan sejumlah kata yang begitu menyentuh. Rahwana ceritakan negara yang tengah di ujung tanduk. Intinya, kekalahan sudah ada di depan mata, dan Kumbhakarna hendaknya bisa member sumbangsih.
Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Kumbhakarna yang berperawakan besar itu akhirnya bangun dari tidurnya. Tampaknya, telinganya yang mirip periuk memang didesain untuk mendengarkan jeritan orang banyak. Ia mendengar kala tanah air memanggil. Mungkin juga berperang untuk orang banyak adalah yadnya yang jadi tiket masuk merengkuh anugerah Brahma.
Kala Kumbhakarna mencoba menasihati Rahwana, sang kakak tak terima. Rahwana sekaan lebih paham soal kebajikan, terlebih soal mengomentari kebijakan raja. Pada kebuntuan itu, tanpa berpikir panjang Kumbhakarna menyatakan siap membela Alengka.
“Aku bertarung bukan untuk membela keserakahanmu, tapi untuk negeri dan tanah airku," katanya memekik dan meninggalkan Rahwana menuju medan laga.
Di medan perang Kumbhakarna menyerang bala tentara Rāma secara membabi buta. Ratusan, bahkan ribuan kera menyerang bersama-sama, namun sia-sia. Para panglima kera, Sang Hanoman, Anggada, Sugriwa, juga Nila tiada mampu menahannya, hingga akhirnya Ramadewa turun tangan. Dihujamkan anak panahnya. Terenggutlah nafas Kumbhakarna sebagai pahlawan Tanah Air Alengka.
Entah, apakah kemudian dalam kematiannya itu Kumbhakarna telah menemukan suka sada yang diidamkan? Tiada yang tahu, tiada yang pernah menuliskan.
Singgasana Kata
Kumbhakarna dalam kegagalannya menemukan suka sada, namun mengakhiri tugasnya di dunia sebagai seorang pahlawan. Melalui kisahnya, kini umat Hindu juga mengenal Dewi Saraswati sebagai dewi yang berstana di lidah. Saraswati yang berasal dari kata ‘saras’ dan berasal dari akar kata ‘sr’ yang berarti ‘mata air’, sesuatu yang mengalir. Aliran air itulah yang kemudian diidentikkan dengan ilmu pengetahuan, yang tiada lain adalah pemberi hidup segala mahkluk.
Kisah Kumbhakarna yang gagal dianugerahi suka sada, namun akhirnya menerima supta sada dari Dewa Brahma tidak lain ingin mengingatkan manusia untuk berhati-hati denga lidah dan ucapan. Ini sejalan dengan pustaka Nitisastra Sargah V.3 yang menyebut, wasita nimitanta manemu laksmi,wasita nimitanta pati kapannguh, wasita nimitanta manemu duhka, wasita nimitanta manemu mitra (oleh perkataan engkau akan mendapat kebahagiaan, oleh perkataan engkau menemukan kematian, oleh perkatan engkau akan diganjar kesedihan, oleh perkataan engkau akan mendapat teman).
Jika demikian, diperlukan kesiapan yang matang dalam menstanakan Saraswati di lidah. Sang Hyang Wagiswari itu tidak bisa distanakan hanya dengan rajah ini dan itu tanpa ada perenungan. Prinsipnya tidak ada pengetahuan yang turun dari langit, tak ada kebahagiaan yang didapat hanya dengan proses ritual tanpa penyuburan ke dalam. Perlu juga segenggam kerendahan hati. Seperti air, kata hanya akan bisa terkumpul ketika wadahnya menengadah dan kosong. Penuh pun tiada cukup, sebab Dharma akhirnya adalah mengalirkannya kembali. Mengalirkan ke wadah yang lain.
_______________
*Penulis adalah Jero Penyarikan Duuran di Pura Ulun Danu Batur, Desa Adat Batur juga Ketua Peradah Indonesia Bangli.
__________________
Kolom Opini Balinesia.id dihadirkan untuk memberi ruang pada khalayak pembaca. Redaksi menerima tulisan opini dalam bentuk esai populer sepanjang 500-1000 kata yang membicarakan persoalan ekonomi, pariwisata, sosial, budaya, maupun politik, yang dapat dikirim ke email [email protected]. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi.